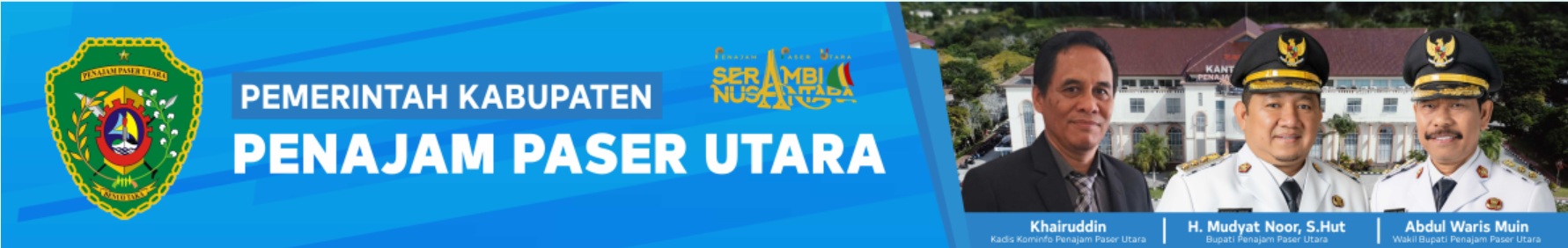Pesantren: Lembaga Pendidikan, Bukan Tempat Reparasi (Refleksi 22 tahun Pondok Pesantren Darul Ishlah)

Oleh : Dr. Abrar Bahari, Lc., MA
OPINI - Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden RI menyarankan agar anak-anak yang susah diatur atau “bandel” supaya dimasukkan saja ke pesantren. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri penutupan Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam (PUI) di Kantor Gubernur Sumut pada Kamis (15/5/2025). Di satu sisi, saran ini menurut penulis sebagai pengasuh pesantren mencerminkan harapan positif terhadap pesantren sebagai institusi pendidikan tertua di negeri ini.
Minat orang tua untuk memasukkan anaknya ke pesantren terus meningkat, mungkin karena mereka masih memandang pesantren sebagai benteng moral yang mampu menfilter anak-anak dari arus negatif budaya modern. Imam Suprayogo (2007), cendekiawan Muslim Indonesia, secara eksplisit menyebut bahwa Pesantren adalah benteng terakhir moral bangsa.
Namun di sisi lain, pernyataan wapres di atas secara tidak langsung berpotensi menghidupkan kembali mindset keliru tentang pesantren, yaitu bahwa pesantren adalah tempat pembuangan, lembaga rehabilitasi anak gagal.
"Kalau masih nakal dan malas, nanti kami masukkan ke pesantren!". Mungkin kita pernah mendengar ancaman semacam ini dari orang tua. Penulis juga pernah didatangi oleh seseorang yang mengeluhkan kenakalan anaknya. Saya lalu menimpali, “Terus, apa langkah Bapak selanjutnya?” Ia pun menjawab, “Saya mau bawa saja ke pesantren.” Saya hanya bisa menghela napas, lalu bergumam, Apa dianggapnya pesantren itu bengkel? Tempat reparasi bagi anak-anak yang tidak bisa lagi ditangani di rumah?
Kerisauan penulis ini menjadi ajakan untuk direnungkan bersama, terutama sebagai orang tua, sebab menurut penulis paradigma seperti ini adalah salah kaprah dan mereduksi makna pesantren secara dangkal. Anak-anak yang patuh dan berprestasi dimasukkan ke sekolah umum sementara anak-anak yang dinilai bermasalah secara kognitif atau sulit dikendalikan di arahkan ke pesantren. Lalu sesudahnya, orang tua berharap sang anak berubah total sim salabim dalam waktu instan.
Sebuah ironi. Seperti ungkapan keprihatinan yang pernah penulis dengar dari almarhum KH. Lanre Said, pimpinan Pondok Pesantren Darul Huffadh, Bone tempat penulis pernah menimba ilmu dahulu- dalam bahasa Bugis: “Pekkoga carana melo jaji? Yakko garope,na mi mutiwiranggi tauwe, nappa santanna mukirim maneng di saliweng?” (Bagaimana bisa cepat behasil, kalau yang kamu bawa ke sini ampasnya saja, sementara santannya kamu kirim semua ke tempat lain?).
Sinergi, Bukan Formula Instan
Pandangan yang menganggap pesantren semacam “bengkel” mungkin perlu dikoreksi. Pesantren bukanlah tempat pelarian bagi anak-anak yang dianggap gagal dibina di rumah dan di sekolah umum. Mulai dari tawuran, kecanduan game, merokok, hingga balapan liar.
Sejak dulu, pesantren dikenal sebagai wadah pembentukan karakter, sumber ilmu, dan pengasah spiritualitas. Di tempat inilah santri digodok sehingga menjadi ulama, pejuang kemerdekaan, dan pendidik umat. Mereka datang bukan karena dibuang oleh orang tuanya, tetapi dikirim dengan doa, cinta, dan harapan. Seperti doa yang dirapalkan oleh Nabi Zakaria: “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.” (QS. Ali ‘Imran: 38).
Namun, yang terjadi kemudian adalah pesantren dituntut dengan ekspektasi instan. Anak diharapkan langsung berubah hanya karena sudah memakai sarung dan peci, sambil menenteng kitab. Pesatren seperti drive-thru: masukin anak di pondok, tunggu tiga bulan, lalu berharap saat diambil sudah jadi ustadz.
Belum lagi intervensi orang tua yang terlalu jauh sehingga menyulitkan proses pendidikan anak. Misalnya, ketika anak mengadu bahwa ia disakiti oleh temannya. Banyak orang tua langsung merespons dan mengambil tindakan sepihak, tanpa tabayyun terlebih dahulu atau mengonfirmasi kepada pihak pesantren. Bisa jadi persoalannya hanyalah miskomunikasi antar teman. Misalnya, temannya hanya bermaksud menegur atau mengingatkan, dan tidak ada tindakan fisik. Tetapi informasi yang sampai kepada orang tuanya tidak seperti itu. Setelah di usut ternyata si anak memang sudah lama tidak betah di pondok Dia hanya mencari-cari alasan atau celah sebagai pembenaran untuk keluar.
Bukan ingin lari dari tanggung jawab, tetapi perlu diingat bahwa mendidik anak adalah pekerjaan yang tidak mungkin ditangani sendirian. Butuh sinergitas antara rumah, pesantren, dan lingkungannya sebagai trias pembentuk karakter. Pesantren hanya akan maksimal jika orang tua juga terlibat aktif, bukan pasif. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan, bukan hanya dalam bentuk kunjungan di hari besuk santri, tetapi dalam bentuk pengertian.
Sebelum memasukkan anak ke pesantren, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu kesediaannya. Orang tua perlu bersikap demokratis dalam hal ini, sebab menurut pengalaman penulis, sekuat apapun keinginan orang tua memondokkan anaknya jika anak itu sendiri tidak memiliki keinginan untuk mondok, maka hasilnya tidak akan maksimal.
Yang ideal itu, jika anak dan orang tuanya punya keinginan dan semangat yang sama. Menurut teori attachment John Bowlby, hubungan yang sehat antara anak dan orang tua tumbuh dari interaksi yang responsif dan tidak memaksakan kehendak. (Bowlby, J. (1998). A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Humant Development).
Akhirnya, mari jadikan pesantren sebagai taman kebaikan yang terus kita jaga bersama. Bukan sebagai bengkel darurat. Pesantren sebagai rumah kedua, kawah candradimuka kesuksesan anak-anak kita ke depannya.
* Tulisan ini disadur dari materi sambutan yang disampaikan pada acara Kesyukuran Milad ke-20, Pondok-Pesantren Darul Ishlah, Tahun 2025